Sejarah Perkembangan Restorative Justice
Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan
dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari
peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam
menyelesaikan masalah termasuk penyelesaan masalah tindak pidana. Istilah umum
tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert
Eglash yang menyebutkan istilah restorative
justice yang dalam tulisannya mengulas tentang reparation menyatakan bahwa restorative
justice adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan
keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.[1]
Sejarah perkembangan hukum modern penerapan restorative justice diawali dari
pelaksanaan program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan
masyarakat yang disebut dengan victim
offender mediation yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara Canada.
Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum
pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban
diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu
pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini mengangap
pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga
akan mendapat perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan
jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak yang
bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Pelaksanaan
program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban
dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.[2]
Perkembangan
konsep restorative justice dalam 20
tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara
seperti Australia, Canada, Inggris, Wales, New Zealand dan beberapa Negara
lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Begitu juga di Amerika Serikat sebagai
sebuah Negara yang sering membentuk perkumpulan dengan Negara-negara untuk
memperkenalkan ukuran penghukuman secara represif tidak dapat menghindar dari
pengaruh kuat perkembangan restorative
justice. keadilan restorative justice
menurut Stephenson, Giller,
dan Brown[3]
terdiri dari 4 (empat) bentuk keadilan restoratif. Semua bentuk tersebut
mempunyai tujuan yang sama yaitu memperbaiki tindakan kejahatan dengan
menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Keempat bentuk
keadilan restoratif tersebut adalah:
1. Victim
Offender Mediation
(VOM)
Proses restorative
justice terbaru adalah victim
offender mediation yang pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di
Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. VOM di Negara
bagian Pennsylvania Amerika Serikat menjalankan program tersebut dalam kantor
pembelaan terhadap korban di bawah tanggung jawab Departemen Penjara. Program
tersebut berjalan dengan sebuah ruang lingkup kejahatan kekerasan termasuk
pelaku yang diancam hukuman mati.
Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu 5
tahun dengan kerangka pengertian dan pemahaman konsep restorative justice yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan
dialog dimana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan
akibat yang ditimbulkan berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan
informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya. Hal itu memberikan
kesempatan kepada korban untuk mendengan dan memberikan kepada pelaku sebuah
kesempatan untuk menerima tanggung jawab perbuatannya dan mengungkapkan
perasaannya tentang kejahatan dan konsekuensi yang diterimanya.
VOM dimulai sekitar tahun 1960 dan yang mana pada tahun 1970
dilaksanakan pada tingkatan local. Pada saat dilakukan di tingkat local itulah
mulai banyak orang direkrut untuk menjadi mediator. Banyak juga yang ditangani
oleh lawyer atau sarjana hukum sukarela dan belum melakukan pertemuan tatap
muka. Tujuan dilaksanakannya VOM adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa
yang terjadi di antaranya membuat sanksi alternative bagi pelaku atau untuk
melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar-benar serius.
Bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya
kepada satu mediator yang merngkorrdinasikan dan memfasilitasi pertemuan.
Peserta yang terlibat dalam bentuk mediasi adalah korban
yang secara sukarela, pelaku, pihak yang bersimpati terhadap kedua pihak,
orangtua/wali dari kedua pihak dan orang yang dianggap penting bila diperlukan
serta mediator yang dilatih khusus.
2. Conferencing/Family
Group Confencering (FGC)
Conferencing dikembangkan pertama kali di Negara
New Zealand pada tahun 1989 dan di
Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran
aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli
New Zealand yaitu bangsa Maori. Proses yang dilakukan masyarakat ini terkenal
dengan sebutan wagga wagga dan telah
dipakai untuk menyelesaikan permaalahan dalam masyarakat tradisional dan
merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Orang yang turut serta dalam
proses family group conferencing adalah anggota masyarakat,
pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak
dari korban atau pelaku serta lembaga yang punya perhatian terhadap
permasalahan anak.
Tujuannya adalah untuk mendapatkan kejelasan dari peristiwa
yang terjadi dengan member semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban,
melakukan reintegrasi korban ke masyarakat, dan pertanggungjawaban bersama.
Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung
dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya
dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan
dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Kemudian meningkatkan kepedulian
pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan
pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannnya. Selain itu bagi keluarga
atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan
membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan
kesempatan kepada korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali
tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh
pelaku terhadap korban.
3. Circles
Pelaksanaan Circles
pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. Circles sama halnya dengan
conferencing yang dalam pelaksanaannya
memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasidi luar korban dan
pelaku utama. Tujuannya membuat penyelesaian terhadp suatu tindak pidana dengan
mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan
dengn terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran yang ingin dicapai melalui proses
Circles adalah terlaksananya
penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan member
kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab
penyelesaian kesepakatan.
Peserta dalam Circles
adalah korban, pelaku, lembaga yang memperhatikan masalah anak, dan masyarakat.
Tata cara pelaksanaan Circle, semua
peserta duduk secara melingkar seperti sebuah lingkaran. Caranya adalah pelaku
memulai dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukannya lalu semua peserta
diberi kesempatan untuk berbicara.
4.
Restorative Board/Youth Panels.
Program ini mulai dilaksanakan di Negara bagian Vermont pada
tahun 1996 dengan lembaga pendamping Bureau
of Justice Assistance setelah melihat respon yang baik dari warga Negara
terhadp studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan
masyarakat dalam program reparative tersebut dan sifat perbaikan menjadi
dasarnya.
Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan
oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga
hakim, jaksa, dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat
bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat.sasarannya adalag peran
aktif serta anggota masayarakat serta langsung dalam proses peradilan tindak
pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat
melakuakn dialog secara langsung dengan pelaku. Pertemuan yang diadakan
tersebut menginginkan pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas
tindakan yang telah dilakukannya.
Masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal konsep
restorative justice dalam kebiasaan, hukum adat serta nilai-nilai yang lahir di
dalamnya. Sebelum dicanangkan di dalam sebuah peraturan khusus di Indonesia,
Negara yang terkenal dengan Pancasilanya ini juga sesungguhnya telah memiliki
konsep restorative justice jauh sebelum ide ini hadir dan
masuk ke dalam sistem peradilan pidana anak.
Pada Sila ke-4 Pancasila, menyebutkan bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Artinya bangsa Indonesia sendiri
telah mengagungkan prinsip
musyawarah sebagai suatu kebiasaan yang mendarah daging untuk
menyelesaikan segala permasalahan yang ada di bangsa ini. Inilah bukti bahwa
sebenarnya restorative justice juga
telah berkembang di dalamnya. Musyawarah akan mencapai suatu kesepakatan yang win-win solution tanpa merugikan atau
menyebabkan ketidakseimbangan terhadap satu pihak sehingga penyelesaian pun
dapat tercapai. Dalam konteksi Indonesia, Bagir
Manan menyebutkan bahwa
konsep dan prinsip
restorative justice sebenarnya telah dipraktekan oleh
sejumlah masyarakat adat Indonesia.57
Braithwaite mengatakan,
“several
years ago in Indonesia I was told of restorative
justice rituals in western Sumatera that ere jointly conducted by a religious
leader and scholar-the person in community seen as having the greatest
spiritual riches and the person seen as having the greatest of learning. My
inclination yhen was to recoil from the elitism of this and insist thet many
(if not most) citizens have the resources (given a little help with training)
to facilitate processesof healing. While I still believe this, I now think it
might be a mistake to seek the persuade Asians to democratize their restorative
juctice practice”.58
(Beberapa
bulan lalu di Indonesia, saya telah menceritakan ritual pendekatan restorative
di Sumatera Barat yang telah diselenggarakan bersama-sama oleh seorang pemimpin
religius dan seorang cendekiawan (orang di dalam masyarakat yang dipandang
mempunyai kekayaan rohani yang terbesar dan orang yang dipandang memiliki
pembelajaran yang terbesar). Kecenderungan saya kemudian melonjak atas elitisme
dari hal ini dan tetap menekankan bahwa banyak orang dari para penduduk atau
warga Negara yang mempunyai sumber daya (dengan diberikan satu bantuan kecil pelatihan)
untuk memfasilitasi proses penyembuhan atau pemulihan. Selagi saya masih
mempercayai hal ini, kini saya berpikir adalah hal yang bisa menjadikan satu
kekeliruan jika berupaya membujuk orang-orang Asia untuk mendemonstrasikan
praktik pendekatan restoratif. Artinya bahwa di dalam kultur bangsa Indonesia
sendiri yaitu khususnya hukum adat telah ada praktik pendekatan restoratif.
Daly and
Immarigeon[4]
menambahkan bentuk-bentuk keadilan restoratif yang berkembang di dunia,
terutama di Amerika Serikat dan Kanada, selain yang telah disebutkan di atas,
yaitu:
1. Hak tahanan dan alternatif selain
penjara
Bentuk keadilan restoratif ini
berkembang sekitar tahun 1970 ketika penjara mengalami ledakan penghuni.
Berkembang kesadaran bahwa tahanan adalah korban dari penyingkiran sosial
masyarakat dai dikriminasi, karen aitu mereka juga harus diberi hak untuk
kembali ke masyarakat dan harus ada alternatif selain penjara.
2. Pilihan penyelesaian sengketa
Berkembang pertengahan tahun 1970,
ditandai dengan gerakan untuk memakai proses yang lebih informal dan turut
melibatkan masyarakat. Alternatif penyelesaian sengketa difokuskan pada
negosiasi, pertemuan korban-pelaku, dan berkurangnya peran para profesional
hukum.
3. Advokasi korban
Keadilan restoratif ini melakukan
advokasi untuk korban tindakan kriminal karena mereka kurang bisa berusara
dalam proses peradilan negara.
4. Justice
Circle
Muncul di Kanada sekitar tahun
1980-an, yaitu proses mencapai konsensus berdasarkan kerangka komprehensif yang
tidak hanya melibatkan korban dan pelaku, tetapi juga keluarga mereka dan
masyarakat.
Dalam konsep hukum pidana positif dalam penyelesaian kasus
pidana, pada umumnya diselesaikan melalui jalur formal, yaitu lembaga peradilan
(litigasi). Jalur ini terkenal dengan
istilah in court system. Dalam
tataran teori, ada tiga hal yang ingin dicapai dari hasil final yang akan
dikeluarkan suatu lembaga peradilan tersebut, yaitu: keadilan, kemanfaatan dan
kepastian hukum.[5]
Meskipun demikian, dalam dataran prakteknya, sangat sulit
ketiganya dapat terpenuhi sekaligus. Adapun hasil yang akan tercipta dari
proses penyelesaiannya dikenal dengan istilah win lose solution, di mana akan terdapat pihak yang menang dan ada
pihak yang kalah. Dengan kenyataan seperti ini, penyelesaian suatu perkara
umumnya kerap menimbulkan satu rasa “tidak enak” di benak pihak yang kalah,
sehingga berupaya untuk mencari “keadilan” ke tingkat peradilan lebih lanjut.
Hal ini pada umumnya dicap sebagai salah satu kelemahan bagi suatu lembaga
litigasi yang tidak dapat dihindari walupun sudah menjadi suatu ketentuan.[6]
Menurut Prof. Mardjono Reksodiputro perdamaian merupakan
inti dari restorative justice. Perdamaian antara korban dan pelaku atau pihak
yang bersengketa serta perdamaian yang dimaksud bertujuan agar keadaan yang
menimbulkan perselisihan atau persengketaan itu bisa di netralisir sehingga
antara korban dan pelaku kembali menjadi seperti semula sebelum terjadi
persengketaan inilah yang di namakan perdamaian. Bahwa perdamaian pada
prinsipnya harus menekankan pada jalan ekspos dan responsibilitas. Ekspos
artinya pelaku membeberkan semua tindakan kejahatannya untuk mendapat respon
dari korban yang diharapkan akan menanggapi dengan lunak. Kemudian mengenai
responsibilitas, memiliki dua elemen yaitu: responsibility
dan abiity. Ability artinya apa yang
mampu dilakukan oleh pelaku dalam merespon tuntutan korban.[7]
Konsiliasi dalam kamus diartikan sebagai permufakatan
(perdamaian), perdamaian atau perdamaian.[8]
Dalam pengertian kamus tersebut, konsiliasi dapat bermakna hasil maupun proses,
sehinga rekonsiliasi dapat diartikan permufakatan kembali atau proses
perdamaian (pendamaian) atau perdamaian itu sendiri, telah terjadi
ketidakdamaian dalam kurun waktu tertentu. Maka dapat dirumuskan beberapa
prinsip yang harus ada dalam sebuah proses perdamaian sebagai berikut :
1. Pengungkapan Kebenaran
Prinsip pengungkapan kebenaran ini
mutlak ada, karena ia adalah gerbang untuk terbukanya pintu perdamian.
Pengungkapan kebenaran menjadi penting karena suatu persoalan tidak mungkin
dapat diselesaikan jika kejadian perkaranya masih dalam misteri, belum jelas
dan simpang siur.
Hak untuk mendapatkan kebenaran (the rights to know the truth) memiliki
payung hukum yang kuat. Hak ini diakui sebagai implementasi dari kewajiban
negara dalam menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam kovenan-kovenan
internasional. Berdasarkan kewajiban inilah kemudian oleh banyak ahli termasuk
dalam praktek yurisprudensi di sejumlah pengadilan Amerika memaknainya sebagai
dasar kewajiban negara untuk mencegah sekaligus melakukan penyelidikan yang
serius terhadap dan menghukum pelakunya dan memberikan kompensasi kepada
korban.[9]
Dalam konteks lain, hak mengetahui
kebenaran bagi korban atau kewajiban mengungkap kebenaran bagi pemerintah juga
muncul sebagai alat untuk melakukan remedy
(upaya penanganan hukum) yang efektif. Perlunya remedy efektif mengandaikan proses pengungkapan kebenaran yang
maksimal melalui media penyelidikan, pemeriksaan, penyidikan maupun pemeriksaan
di Pengadilan. Remedy yang efektif
dapat terwujud jika dilakukan pengungkapan kebenaran baik dalam konteks
pelaksanaan prosekusi maupun dalam kaitannya dengan rehabilitasi dan kompensasi
terhadap korban.[10]
2. Pelurusan Kebenaran
Kebenaran yang diperoleh harus mampu
mengakomodir semua keluhan dari korban dan sesuai dengan keterangan pelaku
sehingga didapatkan satu kebenaran baru yang menjadi tantangan terberat dari
sebuah proses perdamaian.
3. Pengakuan dan Pengampunan
Pengakuan adalah sebuah prinsip
perdamaian yang sangat penting. Pengakuan ini menjadi satu syarat dilakukannya
perdamian dalam bentuk pemaafan (pengampuanan) kepada pelaku. Melalui proses
pengakuan ini, dinyatakan bahwa korban cukup puas dengan adanya pengakuan tulus
dari pelaku dan permohonan maaf, sehingga korban dapat mendengar bagaimana
sebenarnya suatu kejahatan tersebut dapat terjadi sampai pada proses bagaimana
kejahatan itu berlangsung, yang diakhiri dengan permohonan maaf.
4. Pemenuhan Hak-Hak Korban
Hak-hak korban meliputi kompensasi,
restitusi dan Rekonsiliasi. Kompensasi yaitu ganti rugi yang diberikan oleh
pelaku kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya sesuai
dengan kemampuan keuangan pelaku tindak pidana untuk memenuhi kebutuhan dasar,
termasuk perawatan kesehatan fisikn dan mental.
Restitusi yaitu ganti rugi yang
diberikan oleh pelaku kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli
warisnya, sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan harkat dan martabat seseorang
yang menyangkut kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain. Pemenuhan
hak korban adalah satu keharusan mengingat mereka adalah pihak yang menderita,
apalagi jika dikaitkan dengan semangat perdamaian yang memang merupakan sebuah
langkah kebijakan yang diambil sebagai bentuk perhatian kepada korban di
tengah-tengah persoalan tindak kejahatan.[11]
[1] Albert
Eglash, 1977, Beyonde Restitution:
Creative Restitution, Lexington, Massachusset-USA, hlm 95, yang dikutip
oleh Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, Penanggulangan
Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif.
[2] Ibid…hal.30
[3] Martin Stephenson, Henry Giller dan Sally
Brown, Effective Practice in Youth
Justice, Willan Publishing, Portland, 2007, hal. 163-166. Sebagaimana
dikutip dalam DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia, hal. 41.
[4] Kathleen Daly dan Russ Immarigeon, “The Past,
Present, And Future of Restorative Justice : Some Critical Reflections”, dalam Contemporary Justice Review, 1(1), 1998,
hlm. 24-26. Sebagaimana dikutip dalam DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak
Indonesia, hal. 42.
[5] Sudikno
Mentokusumo, Ilmu Hukum Suatu Pengantar,
Liberty Yogyakarta, 1997, hal.98
[6] Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal 3-5.
[7] Lambang
Priyono dalam “Kebenaran VS Keadilan; Pertanggungjawaban Pelanggaran HAM di
Masa Lalu. “Ed. Ifdhal kasim dan Eddie riyadi Terre, Elsam, Jakarta. 2003, hal
70-71.
[8] Pius
A Pratanto dan M. Dahlan Al Barry, “Kamus
Ilmiah Populer”, Arkola, Surabaya, 1994, hal 363.
[9] Yohanes da
masenus Arus, “The Right
to Know the
Truth; Kerangka Normatif Pengungkapan Kebenaran”, dalam
Yohanes dkk. Op.cit., hal 337.
[10] Ibid..
[11] Mahrus
Ali, Syarif Nurhidayat, Penyelesaian
Pelanggaran HAM BERAT In Court System
& Out Court System, Jakarta : Gratama Publishing, 2011, Hal 301.
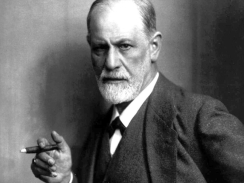

Komentar
Posting Komentar